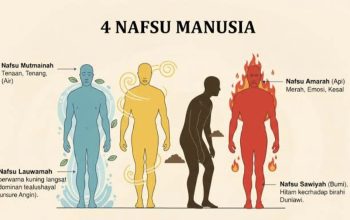Di Balik Dinding Rumah: Fantasi Sedarah dan Kegagalan Perlindungan
Oleh : Syaifa Putri
Departemen Eksternal Kohati Cabang Sumenep
________________________________
ARTIKEL – Kekerasan seksual masih menjadi isu serius yang menuntut perhatian bersama, seolah tak ada habisnya. Selama ini, narasi publik sering kali secara keliru menggambarkan perempuan sebagai satu-satunya korban, seolah-olah jenis kelamin tertentu telah dipatenkan sebagai sasaran kekerasan. Padahal, kebenarannya jauh lebih kompleks. Siapa pun, terlepas dari jenis kelaminnya, bisa menjadi korban, dan siapa pun juga bisa menjadi pelaku. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang kekuasaan dan kesempatan.
Kasus yang baru-baru ini mencuat terkait grup Facebook “Fantasi Sedarah” menjadi contoh nyata bagaimana ruang digital yang mestinya menjadi jembatan informasi, justru bisa menjadi arena kejahatan seksual yang mengerikan. Bayangkan, rumah ruang tempat anak semestinya belajar, bermain, dan tumbuh dengan aman malah menjadi arena pencabulan oleh orang tuanya sendiri.
Grup Facebook ini diikuti lebih dari 3.200 anggota, berisi fantasi seksual yang melibatkan ayah, ibu, dan anak, serta sekumpulan orang dengan fantasi liar yang sulit diterima akal sehat. Tak hanya teks, bahkan ada sebaran foto-foto yang menggambarkan anak-anak dan keluarga mereka secara seksual. Sungguh menyayat nurani, keluarga yang mestinya menjadi tempat penuh kasih dan perlindungan, malah menjadi sumber teror paling mengerikan.
Pada hari Selasa, 21 Mei 2025, pihak Kepolisian berhasil menangkap 32 orang pelaku di berbagai lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Saat ini, para pelaku diamankan di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Beberapa di antaranya terbukti sebagai admin dan anggota aktif yang mengunggah konten tak bermoral tersebut. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDITI) telah melakukan langkah pemblokiran sebagai upaya memutus akses terhadap konten bejat ini.
Kejahatan menyebarkan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ini adalah cerminan telanjang dari kegagalan sistem pendidikan, perlindungan sosial, dan bahkan pengawasan digital kita. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini dapat dikenai pasal-pasal berat.
Pelaku dapat dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di bawah umur, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.
Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan konten tersebut juga melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang distribusi dan penyebaran konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jika terbukti menyakiti martabat dan hak asasi anak, pelaku dapat dijerat dengan pidana berlapis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lalu, apa yang salah di negeri ini? Mengapa bangsa yang religius dalam simbol bisa gagal mencegah kekejaman di ruang privat? Mengapa anak-anak yang semestinya diasuh dengan cinta justru diperlakukan seperti objek pelampiasan?.
Apakah ini karena orang tua yang belum matang secara emosional dan secara mental belum siap menjalankan peran yang berat? Atau apakah kita terlalu terpaku pada norma sosial dan budaya yang menaburkan pembicaraan tentang seksualitas dan kesehatan mental dalam keluarga?.
Ada juga yang menyalahkan kebebasan akses informasi dan maraknya pornografi sebagai penyebab kerusakan moral generasi muda. Namun, kita perlu mempertanyakan kembali: apakah internet yang bersalah, atau justru kita yang belum mampu mengajarkan anak-anak dan masyarakat tentang cara memanfaatkan teknologi secara benar dan bertanggung jawab?.
Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan adalah nilai dan pendidikan yang kita tanamkan sejak dini. Jika kita gagal mendidik dengan benar, maka kita hanya akan membuka celah bagi kekerasan dan kejahatan untuk terus berkembang, bahkan di balik dinding rumah sendiri.
Kita juga perlu sadar bahwa pelaku kekerasan tidak lahir dari ruang hampa. Mereka, para ‘pelaku’ ini, dulunya adalah anak-anak yang pernah dianggap suci. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang mungkin saja penuh kekerasan, minim pendidikan moral, atau tanpa bimbingan emosional yang memadai. Trauma dan pola perilaku yang tidak sehat dari masa lalu bisa menjadi benih bagi tindakan kejahatan di masa depan.
Maka, tidak cukup hanya menghukum pelaku.
Yang lebih mendesak saat ini adalah bagaimana kita membangun sistem pemulihan yang utuh bagi para korban. Sebab, seberat apa pun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, trauma korban tidak pernah hilang begitu saja. Luka yang ditorehkan oleh kekerasan seksual seringkali menetap seumur hidup, menghantui psikis dan masa depan mereka. Program rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum yang berkelanjutan, dan dukungan sosial bagi korban adalah mutlak.
Jika kita sungguh ingin membangun masyarakat yang sehat dan melindungi generasi penerus, maka kita harus berhenti menyalahkan satu-dua faktor. Kejahatan seksual adalah kegagalan kolektif: gagal mendidik, gagal melindungi, dan gagal membangun ruang yang aman. Untuk terciptanya keteraturan sosial dan kesejahteraan di negeri ini, diperlukan kerja sama dari semua dimensi: individu, komunitas, dan negara.
Individu:
Setiap orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membekali anak dengan literasi digital yang memadai. Ini termasuk kemampuan anak untuk mengidentifikasi dan melaporkan konten atau perilaku yang tidak pantas, serta membangun komunikasi terbuka dengan orang tua.
Komunitas:
Peran aktif masyarakat, mulai dari tetangga, sekolah, hingga tokoh agama sangat krusial dalam menciptakan jaring pengaman sosial. Komunitas dapat menjadi mata dan telinga, memberikan edukasi preventif, dan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi anak-anak. Program-program pencegahan berbasis komunitas, seperti forum diskusi orang tua atau pelatihan pengenalan dini kekerasan seksual dan pendidikan seksualitas yang komprehensif, perlu digalakkan.
Negara:
Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku, tetapi juga pada reformasi sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi korban, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial, serta kampanye edukasi nasional yang masif tentang pencegahan kekerasan seksual dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.
Optimalisasi peran Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDITI) dalam pengawasan konten internet dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban adalah kunci.
Faktanya, lingkungan tidak cukup mendidik secara mandiri. Misalnya, jika seseorang terjun ke masyarakat yang bobrok, ia pun akan terpengaruh dan bisa turut memperburuk kekurangan tersebut. Sebaik apa pun masyarakat, jika dipimpin oleh rezim zalim yang tidak menyejahterakan rakyatnya, maka apalah arti dari kebaikan-kebaikan lainnya. Ini adalah tugas bersama, membangun sistem yang kuat dari hulu ke hilir.
Dan satu hal yang paling penting, “rumah harus kembali menjadi tempat yang aman, bukan ruang penuh teror.” Karena jika anak tidak aman di rumahnya sendiri, di tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan, maka masa depan bangsa ini pun terancam runtuh dari dalam.