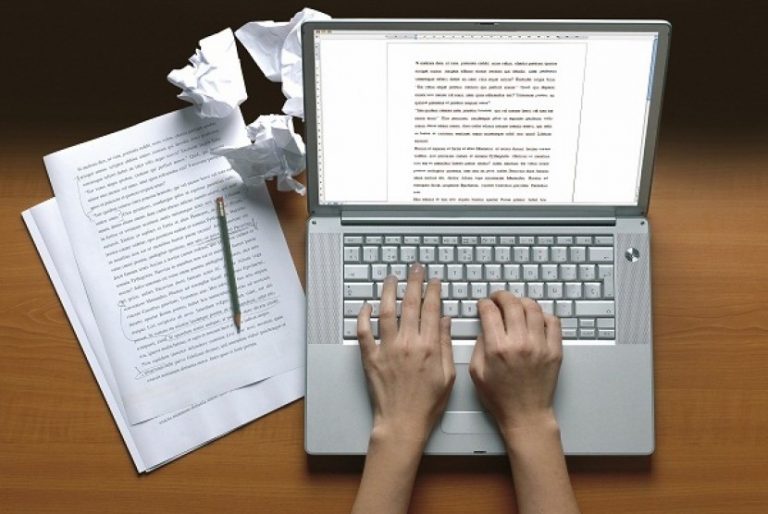Senin, 14 Oktober 2019.
LIMADETIK.com, Cerpen oleh: Yant Kaiy
Guru yang ditugaskan di daerah pedalaman atau di sebuah pulau terpencil bukan lagi hal yang aneh. Karena itu, Ayah dan Ibu menyarankan agar saya menerima tugas suci itu dengan lapang dada.
Namun dalam hati kecil saya bertolak belakang dengan saran-saran beliau. Apalagi menerimanya.
Sama sekali saya tidak menyangka akan ditugaskan menjadi guru di Pulau Madura. Mengapa saya enggan menerima tawaran itu? Pertama, karena tempatnya jauh dari tempat tinggal saya. Kedua, saya mendengar dari mulut ke mulut masyarakat Madura suka carok.
Seperti yang disarankan Bu Jamilah, tetangga kami.
“Lho, kapan berangkatnya?” tanya Bu Jamilah ketika kami berpapasan di jalan.
“Gagal, Bu,” jawab saya sekenanya.
“Itu jalan terbaik, Ning!”
“Kenapa?”
“Orang-orang di sana kasar dan kalau bertengkar selalu bawa celurit”.
Sebenarnya saya juga sering membaca komik atau cerita rakyat yang mengisahkan Pak Sakera dari Tanah Merah. Ia identik dengan celurit. Begitulah, akhirnya kengerian terhadap carok mendorong saya malas menerima tugas sebagai guru.
Menganggur lebih baik, ketimbang nanti di sana saya sering melihat darah. Tak terbayangkan kengerian itu. Merinding jadinya. Saya trauma dengan darah, apalagi darah manusia. Darah binatang saja saya ngeri.
Ketika saya mengungkapkan keputusan saya kepada Ayah, ternyata beliau menangkal keputusan yang telah saya buat. Seperti tadi pagi ketika kami sarapan bersama.
“Kau mau kerja apa, Elli? Selama tiga tahun kau menganggur. Bukankah hal itu merupakan kesempatan terbaik!?” cetus Ayah.
“Tapi,” saya mencoba memotong pembicaraan Ayah.
“Ayah paham dan sangat mengerti. Kau jangan langsung menelan mentah-mentah omongan orang.
Bulatkan niatmu bahwa kamu ingin mengajar. Bukan ber-carok. Atau mencari musuh!” Ayah berhenti sejenak menghela napas. “Dan tak mungkin kamu di sana dimusuhi orang. Percayalah!”
Ada benarnya juga, gumam saya membatin. Sehingga timbul keberanian untuk menerimanya. Tapi keraguan kadang ternatal di benak ini meski gempurannya tidak sehebat sebelumnya. Menerima tugas atau tidak membutuhkan akal-pikiran jernih.
Tugas ini datangnya mendadak, dua hari yang lalu. Dan saya harus berangkat besok pagi. Mau tidak mau saya harus mematangkan batin. Saya harus meneguhkan keputusan sebelum semuanya buyar tak berbekas.
Malam kian larut. Jam dinding menunjuk angka dua. Suara-suara burung malam, jangkrik, hembusan angin malam menggerakkan dedaunan yang ada, bunyinya mengisi kekosongan sepi. Suara itu seolah meninabobokan manusia. Tapi bagi saya suara itu bagai suara darah yang mengalir dari sesosok tubuh yang tergolek di tanah merah, sehingga bulu roma saya berdiri tegak.
Keraguan itu datang silih berganti.
Kadang perasaan takut dan ngeri pupus seketika mengingat ketidaknyamanan sebagai pengangguran. Menjadi guru di sana, disamping mengajar dan menjadi guru, juga menambah keingintahuan saya tentang Pulau Garam yang termasyhur akan caroknya. Kalau saya tidak menerima tawaran ini, maka selama hidup saya tidak akan pernah tahu Pulau Madura.
Pagi masih berkabut. Tapi kendaraan sudah mulai ramai. Saya telah menginjakkan kaki di bumi Madura setelah dua hari satu malam berada di tengah laut. Tak pernah terlukiskan sebelumnya, ternyata Madura hampir sama dengan daerah saya, Pomala, Sulawesi Tenggara.
Dari Kota Sumenep saya naik angkutan mobil dinas ke sebuah Desa Prancak. Cukup jauh juga dari Sumenep.
“Desa ini masuk kecamatan apa, Pak?” tanya saya pada sopir yang tetap fokus pandangannya ke depan.
“Kecamatan Pasongsongan, Bu.”
“O ya. Masih jauh, Pak?”
“Sebentar lagi.”
Sudah tiga hari saya berada di Desa Prancak. Saya tinggal di perumahan guru yang berdekatan dengan tempat mengajar. Guru-gurunya banyak yang berasal dari Madura. Selama tiga hari pula Pak Sularso yang selalu mengajak saya jalan-jalan di desa ini.
“Gimana, betah tinggal di sini, Bu?”
“Alhamdulillah, Pak,” pintas saya.
“Syukurlah,” ujar Pak Sularso kepala sekolah kami.
“Ternyata tak ada carok ya, Pak.”
Lelaki itu tersenyum, manis. Ada kilat teduh pada sinar matanya. Mungkinkankah saya telah jatuh cinta dengannya. Ah, tidak.
“Itu dulu, Bu. Sekarang sudah tidak ada.”
Ketika mata kami bersirobok, ada getar aneh menyelinap di hati. Dan tangan kami menyatu dalam angin kemarau yang berhembus kencang. Carok kami adalah cinta, bukan darah.
Sanggar Adinda Pasongsongan, Sumenep.